Suatu hari saya
mendapat tugas turun lapangan ke sekoloah untuk mencari beberapa siswa yang
membutuhkan bantuan. Setelah mendapatkan ijin dari sekolah yang dituju kami
mencari siswa-siswa yang membutuhkan bantuan dengan cara menggunakan database
dari sekolah mengenai siswa-siswa yang perlu perhatian lebih. Singkatnya saya
mendapat klien anak SD kelas 4. Saya tidak akan menceritakan kasusnya seperti
apa tapi yang saya soroti adalah orang tuanya. Sebelum melaksanakan assessment
psikologi saya dan sekolah meminta persetujuan kepada orang tua klien dan
mereka mengijinkan.
Asesmen berjalan lancar
walaupun orang tuanya agak susah ditemui. Jadi saya melakukan sebagian besar
wawancara kepada orang tua di sekolah. Hingga
tibalah saat psikotes. Malam harinya orang tua memberitahukan bahwa klien tidak
bisa ikut psikotes karena akan diajak ortunya ke luar kota. Esoknya ternyata si
klien ini masuk sekolah. Ayahnya bilang ke wali kelas kalau anaknya tidak bisa
ikut psikotes karena akan dijemput pukul 12.00 dan berangkat keluar kota.
Sedangkan psikotes dimulai pukul 8.00-10.00. Menurut wali kelas, klien tetap
bisa ikut psikotes karena ada selisih waktu 2 jam antara selesai psikotes dan
waktu penjemputan klien dari sekolah.
Singkat cerita setelah
mengalami adu argumen antara wali kelas dan ayahnya klien, si klien diijinkan
ikut psikotes. Pukul 8.00 saya mulai psikotes hingga pukul 9.30 si ibu menelpon
saya dengan marah-marah. Intinya dia sudah bilang kalau anaknya tidak bisa ikut
psikotes hari itu tapi kenapa tetap diikutkan. Setelah berdebat dengan si ibu
dan ia memaksa untuk menjemput anaknya saat itu juga, ya terpaksa saya kabulkan
karena itu orang tua klien. Untungnya hanya tes grafis yang belum saya berikan
kepada si klien pada saat itu. Akhirnya saya melakukan tes grafis di lain
waktu.
Setelah hasil psikotes
keluar, IQ normal, kepribadian tidak ada gangguan terhadap si anak, dan hasil
lainya saya sampaikan kepada sekolah dan orang tua secara terpisah. Ketika saya
menyampaikan kepada orang tua, pihak orang tua meminta agar hasilnya tidak
disampaikan kepada sekolah dengan alasan takut mempengaruhi nilai anak dan pandangan
pihak sekolah terhadap si anak. Si ibu takut bahwa anaknya di cap anak yang
bermasalah secara psikologis.
Pengalaman
ini memberi saya banyak pelajaran. Pertama, tentang mindset masyarakat kita
tentang gangguan psikologis dan gangguan lainya. Tanpa disadari, masyarakat
kita masih mengkotak-kotakan orang-orang dan memberi label. Labeling ada untung dan ruginya.
Keuntunganya ketika seorang anak sudah diketahui gangguan psikologisnya akan
lebih mudah penangananya. Ruginya, dengan labeling
ini, individu terlabel akan merasa lebih terdiskriminasi oleh masyarakat. Bahkan
banyak masyarakat yang menyembunyikan identitas keluarganya yang mengalami gangguan
psikologis akibat adanya labeling dan
diskriminasi. Saya mau tahu dan memahami alasan keluarga yang melakukan hal
ini. Karena siapa sih yang mau jadi berbeda dan dibedakan. Berbeda dalam arti
yang kurang baik menurut penerimaan sebagian masyarakat. Banyak sanksi sosial
yang akhirnya dirasakan oleh keluarga atau individu yang memiliki gangguan
psikologis. Mereka harusnya diayomi bukan didiskriminasi.
Kedua,
ternyata bagi sebagian orang, psikotes adalah sebuah momok tersendiri. Banyak
orang yang enggan melakukan psikotes dengan alasan takut sisi “lain”nya
terkuak. Seolah-olah dengan adanya psikotes ini semua rahasia akan terbongkar.
Ya tidak seperti itu, dikira kita para praktisi psikologi ini dukun. Padahal
semakin cepat kita tahu ada atau tidaknya gangguan psikologis akan berguna bagi
kita. Kita akan berupaya melakukan tindakan pencegahan atau penyembuhan atas
gangguan tersebut.
Ketiga,
bagi masyarakat, semua gangguan psikologis disamaratakan. Gangguan psikologis
dianggap sebagai gila. Jadi orang yang mengidapnya akan menjadi ORANG GILA. Padahal
tidak semua gangguan psikologis itu sama seperti arti orang gila seperti yang
ada di pikiran masyarakat. Bahasa ilmiahnya mereka menggeneralisasikan semua
gejala dalam sebuah istilah tertentu.
Walaupun
saat ini gaung tes psikologi dimana-mana, di rekrutmen, penerimaan siswa, dan
berbagai hal lainya tapi belum memberikan wawasan yang benar tentang psikotes
itu sendiri. Solusinya bagaimana agar masyarakat ini paham tentang wawasan
psikotes yang benar? Sebenarnya perangkat masyarakat adalah wadah untuk
mewujudkan itu. Tapi penyuluhan saja sepertinya tidak berpengaruh besar. Wawasan
ini bisa juga di dapat dari obrolan non
formal yang memperbaiki mindset. Misal, perangkat desa/lurah memberikan
penyuluhan pada kegiatan PKK atau perkumpulan rutin. Jadi, perkumpulan ini tak
hanya soal demo masak, beauty class,
tanaman toga, atau bahkan gunjingan yang merugikan. Ada upaya perubahan mindset. Memang hasilnya tidak bisa
langsung dirasakan dalam waktu dekat. Karena mengubah mindset tak sehari dua hari. Manusia butuh pengulangan, manusia
butuh waktu apalagi kalau mindset ini di perkuat oleh lingkungan sekitar.
Sebenarnya,
kalau mau jujur, sebagian masyarakat ini sudah tahu kok tentang wawasan yang
benar tentang gangguan psikologi dan tes psikologi. Tapi ada yang tahu tapi tak
mau jadi tetap saja perilakunya sama walaupun pengetahuannya bertambah. Apakah
mindset berubah? Belum tentu. Ya secara pengetahuan dia berubah dari tidak tahu
menjadi tahu. Tapi mengubah dari tidak mau menjadi mau ini susah karena
melibatkan preferensi
(kecenderungan/kesukaan) yang berhubungan juga dengan mindset kita.
Jadi,
sebagai orang-orang yang sudah terpapar arus internet dan informasi hampir di
setiap detik kehidupan kita, baiknya kita ikut memperkaya diri dengan wawasan
itu dan tidak iku-ikutan jadi orang yang salah kaprah menerjemahkan gangguan
psikologi maupun tes psikologi ke dalam satu hal yang sama yaitu Kegilaan.

![[ BOOK REVIEW ] THE CELESTINE PROPHECY (MANUSKRIP CELESTINE) BY JAMES REDFIELD](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB8HZ2vO6USCJVzHettXQMNbaa7ZoHaTl2vusuaM2vcVX7Lxa9RwsB22g0TPbYw3rR0u9NLUfGpd3LgWoUQm4dEbOfeYEySfFoHNkpdF43bZOCT9GToTRa9VZpvTUdjfitwQ-tHumACKg/s72-c/WhatsApp+Image+2018-12-10+at+11.56.21.jpeg)
![[ BOOK REVIEW ] KAMBING DAN HUJAN BY MAHFUD IKHWAN : LEBIH DARI SEKEDAR "ANGON" KAMBING](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkvB1z6s_OFkHe9_dLxU8lhl5u1-T92UVHpOPKMAA1CFblWnq9t25cykFrItwV5w3vvOUAHv7jmR1n8vHF2CGQYylOb-GeUsAY3yvC0VwJBrvI5AGdjkAxBm_4wmhEXCpY7yvpuBlwx2g/s72-c/IMG_20191027_102250_HDR.jpg)
![[BOOK REVIEW] KAGUM KEPADA ORANG INDONESIA: UNIKNYA ORANG INDONESIA](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi457j310WP-Z1OJhOmCQqEU-VjuGnqGZo2Ja0LQJhdAF5IsItIROLYOUMxKSVd1HEV0CPa3tourGgNoHixcoM7yvNa2eFaKcT9XWnOtWsui9_6YzuQbkSewAJubknWIOSn24TD5aE9UOw/s72-c/WhatsApp+Image+2021-02-19+at+18.15.25.jpeg)
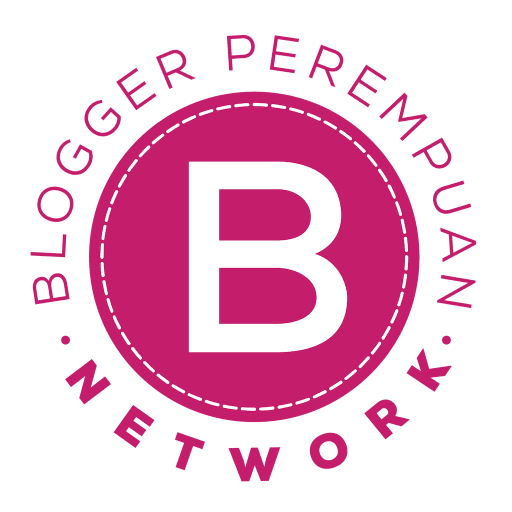
0 komentar